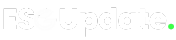ESG Update, Jakarta – Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menyatakan bahwa periode 2025 hingga 2030 seharusnya menjadi momen krusial dalam perjalanan transisi energi di Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat membawa Indonesia mencapai target energi terbarukan lebih dari 40% dan menurunkan puncak emisi sektor energi pada tahun 2030.
“Keberhasilan mencapai bauran energi terbarukan yang ambisius dalam dekade ini sangat penting untuk mengharmonisasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Indonesia sesuai dengan Persetujuan Paris guna membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 1,5 derajat Celsius,” ujar Fabby dalam keterangan pers, Kamis (1/2/2024).
Fabby menyoroti bahwa penetapan target baru EBT ini tidak sejalan dengan target bauran energi terbarukan dalam kesepakatan Just Energy Transition Partnership (JETP), yang menargetkan bauran EBT sebesar 44% pada tahun 2030.
“JETP telah menyepakati target bauran energi terbarukan di atas 34% di 2030 dan target ini selaras dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang dibahas berbarengan dengan Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) tahun lalu,” kata Fabby.
IESR merasa bahwa target bauran energi terbarukan yang diusulkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DEN) dapat meragukan kredibilitas arah kebijakan transisi energi Indonesia di mata investor dan dunia internasional.
“Daripada menurunkan target dengan alasan realistis, DEN seharusnya mengambil pendekatan yang lebih progresif dalam melakukan transisi energi,” tandas Fabby.
IESR juga berpendapat bahwa DEN seharusnya mengatasi hambatan koordinasi, tumpang tindih kebijakan, dan prioritas yang dapat mempercepat perkembangan energi terbarukan dan efisiensi energi.
IESR menilai beberapa strategi dalam Rencana Pembangunan Ketenagalistrikan (RPP KEN), seperti pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berkapasitas 250 MW pada 2032 dan penerapan Carbon Capture and Storage (CCS/CCUS) pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang masih beroperasi hingga 2060, belum didasarkan pada kelayakan teknis dan ekonomis di Indonesia saat ini.
“PLTN dengan kapasitas kecil dari 300 MWe, small modular reactor, masih belum tersedia teknologi yang terbukti aman dan ekonomis,” imbuh Fabby.
Fabby menyatakan bahwa teknologi PLTN dengan kapasitas kecil dan penggunaan CCS/CCUS pada PLTU masih memerlukan persiapan infrastruktur institusi, kesiapan regulator, standar keamanan, serta teknologi yang teruji dan persetujuan masyarakat sebelum implementasinya.
“Adapun aplikasi CCS/CCUS pada PLTU hingga saat ini masih menjadi solusi mahal dan tidak efektif untuk menangkap karbon, walaupun teknologi ini sudah dikembangkan puluhan tahun,” pungkasnya.
Sementara itu, Deon Arinald, Manajer Program Transformasi Energi IESR, mengungkapkan Indonesia akan terbebani dengan biaya penerapan carbon capture and storage (CCS) pada PLTU yang mahal. Selain itu biaya operasional yang rentan volatilitas serta tidak berkelanjutan. Sedangkan pembangunan PLTN menjadi antiklimaks di tengah menurunnya kapasitas PLTN dunia setelah tragedi nuklir di Fukushima.
“Pada dekade ini, seharusnya strategi mitigasi emisi GRK Indonesia pada sektor energi dapat difokuskan pada pembangunan teknologi energi terbarukan dan energy storage yang sudah terbukti dapat menyediakan energi dengan biaya kompetitif dengan PLTU batubara yang masih dapat subsidi,” kata Deon.
Deon memandang, bahwa Indonesia seharusnya lebih fokus mempercepat ekspansi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).
“Pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki adalah bagaimana menyiapkan pipeline proyek-proyek yang siap untuk diinvestasikan serta proses pengadaan di PLN,” jelasnya.